Hijrah, Validasi, dan Poligami: Ketika Kesalehan Menjadi Performa Digital
Analisis mendalam tentang poligami modern, fenomena hijrah, dan kebutuhan validasi sosial di era digital—untuk mengajak pembaca merenungi perbedaan nyata antara sunnah dan performa.
GAYA HIDUPSUDUT PANDANG
11/26/20257 min read
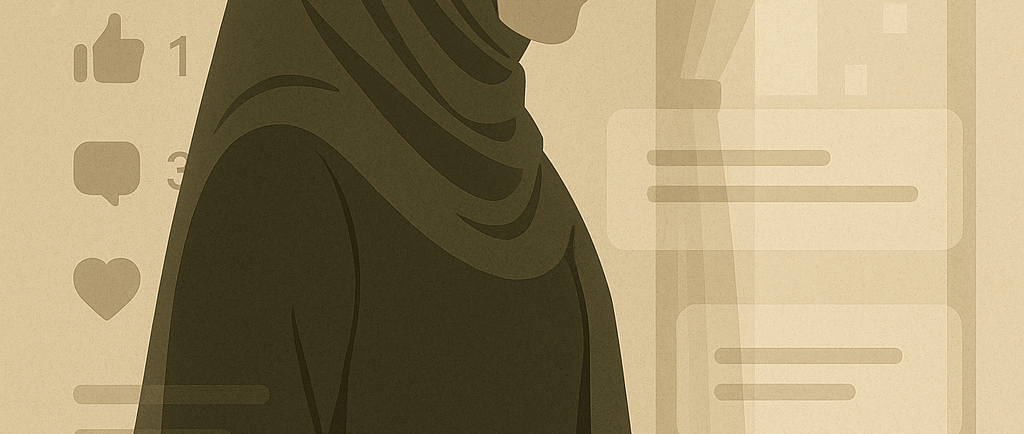

Pendahuluan: Ketika Kesalehan Berubah Menjadi Pertunjukan
Dalam beberapa tahun terakhir, ruang digital Indonesia dipenuhi wajah-wajah baru yang tampil religius: unggahan kajian, busana syar’i, kutipan ayat, dan narasi hijrah yang begitu indah. Pada satu sisi, ini perkembangan yang menggembirakan. Namun di sisi lain, muncul fenomena yang mengganggu—ketika kesalehan berubah menjadi performa, dan dalil agama berubah menjadi teknik legitimasi.
Salah satu bentuk paling nyata dari pergeseran itu muncul dalam praktik poligami modern. Bukan poligaminya yang menjadi masalah, melainkan caranya:
sering dimulai dari hubungan gelap, dilanjutkan dengan nikah siri, dan diakhiri dengan pembenaran menggunakan kisah-kisah Nabi.
Agar dapat memahami ini dengan jernih, perlu melihat kembali bagaimana poligami dipahami dalam sejarah, lalu membandingkannya dengan gejala sosial yang terjadi hari ini.
1. Jejak Pernikahan Rasulullah: Monogami Sebagai Dasar, Bukan Pengecualian
Sering kali perdebatan poligami diwarnai klaim: “Nabi poligami, maka ini sunnah.”
Namun catatan sejarah justru menunjukkan:
Rasulullah ﷺ hidup lebih dari dua dekade sebagai suami satu istri.
Selama masa itu:
pernikahan berlangsung harmonis,
tidak ada istri kedua,
tidak ada wacana poligami,
dan tidak ada indikasi keinginan menambah pasangan.
Inilah fase terpanjang dalam perjalanan rumah tangga beliau.
Jika ingin meneladani Nabi secara utuh, maka titik berangkat yang paling masuk akal adalah kesetiaan dan stabilitas rumah tangga beliau, bukan fase poligami yang datang jauh belakangan dan dalam situasi kompleks.
Monogami Nabi bukan hasil keterbatasan, tetapi pilihan akhlak.
Dan itu bagian dari sejarah yang sering diabaikan.
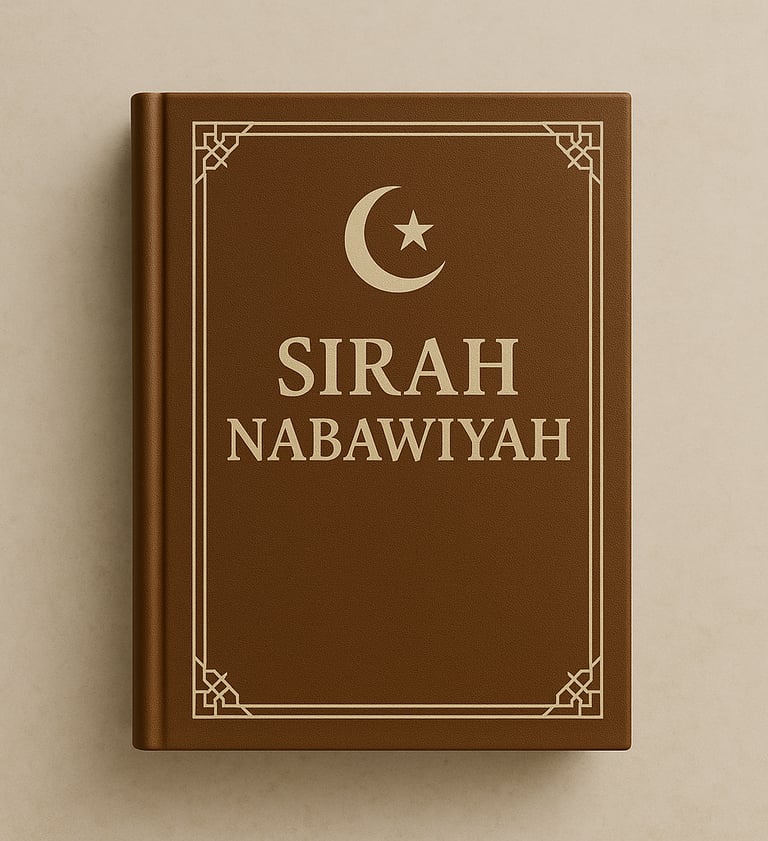
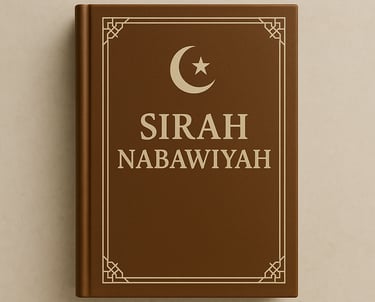
2. Setelah Khadijah Wafat: Poligami Nabi Sebagai Beban Sosial, Bukan Pelarian Emosional
Fase poligami Rasulullah baru dimulai setelah Khadijah wafat. Pada periode Madinah, umat berada dalam kondisi:
dilanda peperangan,
banyak perempuan menjadi janda,
banyak keluarga kehilangan pelindung,
dan struktur sosial perlu direkatkan kembali.
Dalam kondisi inilah poligami Nabi muncul—sebagai strategi kemanusiaan, bukan romansa.
Banyak istri Nabi adalah janda yang kehilangan keluarga dalam perang, perempuan tua, atau perempuan yang memerlukan perlindungan sosial. Pernikahan itu adalah beban, bukan hiburan.
Sesuatu yang jelas berbeda dengan beberapa fenomena poligami modern yang justru lahir dari ketertarikan pribadi, kenyamanan emosional, atau perselingkuhan yang dibungkus istilah “proses taaruf”.
3. Kisah Juwayriyah binti al-Harits: Dalil yang Kerap Diseret Keluar dari Konteks
Kisah pernikahan Nabi dengan Juwayriyah binti al-Harits sering dipakai untuk membenarkan poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama.
Disebutkan bahwa Aisyah r.a. mendengar kabar itu dari masyarakat, bukan dari Nabi secara langsung.
Sekilas, seolah ada legitimasi untuk “tidak izin”.
Namun konteksnya menunjukkan cerita yang jauh lebih luas.
a. Pernikahan di Tengah Perang, Bukan di Belakang Layar
Juwayriyah adalah tawanan perang Bani Musthaliq. Ia datang kepada Nabi untuk meminta pembebasan dari status tawanan. Rasulullah:
memerdekakannya,
lalu menawarkan pernikahan sebagai perlindungan sosial,
dan akad itu dilakukan terbuka di tengah pasukan, bukan diam-diam.
Tidak ada hubungan gelap, tidak ada komunikasi rahasia.
b. Mengapa Aisyah r.a. Mendengar dari Masyarakat?
Masyarakat Madinah bersifat komunal. Informasi publik bergerak cepat.
Pernikahan Nabi dengan Juwayriyah adalah peristiwa sosial besar; wajar jika kabarnya tersebar sebelum percakapan rumah tangga terjadi.
Ini berbeda dengan era sekarang, ketika nikah siri dilakukan:
di luar pengetahuan istri pertama,
disembunyikan bertahun-tahun,
atau baru diakui setelah ketahuan.
c. Dampak Sosial: Pembebasan Tawanan
Pernikahan itu membuat para sahabat membebaskan seluruh tawanan Bani Musthaliq karena tidak ingin “keluarga Nabi” menjadi budak.
Akibatnya, ratusan orang merdeka.
Dengan kata lain:
pernikahan ini adalah kebijakan sosial, bukan pembelaan terhadap hubungan pribadi.


4. Poligami Modern: Ketika Dalil Mulia Digunakan untuk Menyelamatkan Perilaku Gelap
Kontras dengan konteks Nabi, banyak poligami modern muncul dari pola yang sama:
a. Kedekatan emosional di ruang hijrah
Di mana perempuan baru hijrah mencari bimbingan, dan laki-laki yang lebih mapan menjadi objek kekaguman spiritual.
b. Komunikasi pribadi yang ditutup-tutupi
Dimulai dari curhat, kemudian ada rasa nyaman, lalu hubungan emosional.
c. Nikah siri sebagai “pembenaran syar’i”
Sering dilabeli “sunnah”, padahal sebelumnya ada pengkhianatan.
d. Keterlambatan mengakui kepada istri pertama
Bukan karena ingin menjaga perasaan, tetapi karena takut konsekuensi sosial.
Pada tahap ini, poligami bukan lagi ibadah, tetapi jalan keluar dari hubungan gelap yang terlanjur jauh.
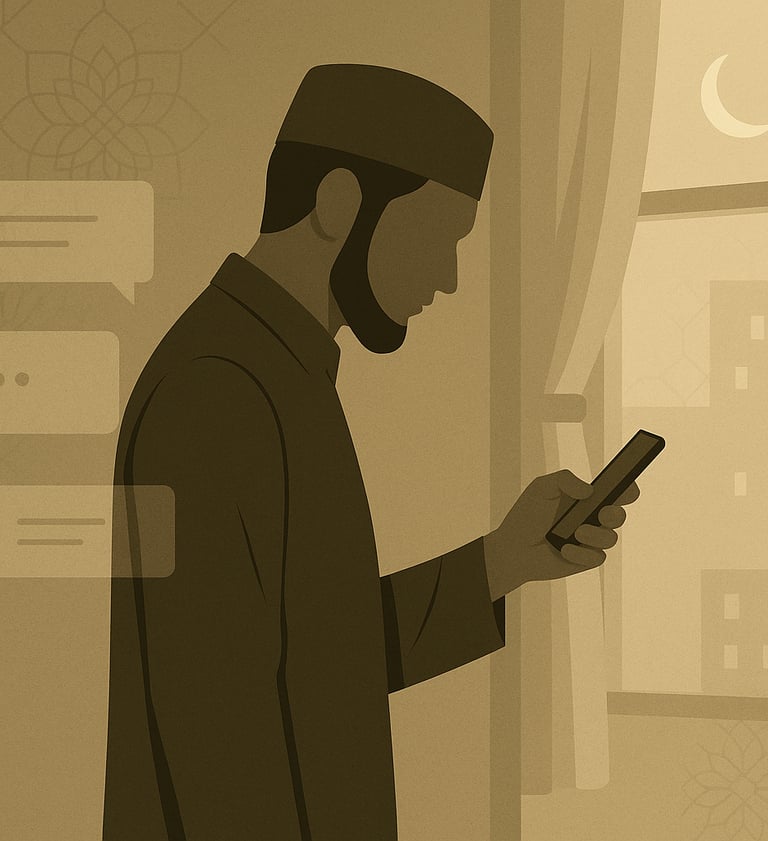

5. Fenomena Perempuan Kedua yang Membutuhkan Validasi:
Mengapa Polanya Mirip di Banyak Tempat?**
Penulis tidak bermaksud menghakimi, tetapi mengamati gejala yang berulang.
Dalam banyak kasus, perempuan kedua datang dari latar hijrah baru dengan karakteristik:
a. Butuh bimbingan spiritual
Ini membuat mereka menempatkan laki-laki religius sebagai figur ideal.
b. Terjebak antara kesalehan dan kebutuhan eksistensial
Karena nikah siri tidak memberi mereka:
status,
legalitas,
keamanan finansial,
atau rasa aman,
maka muncul dorongan untuk memastikan diri:
meminta suami mengumumkan poligami,
meminta status diperjelas,
bahkan mem-posting kemesraan terbatas (close friends, story privat) sebagai sinyal “saya ada”.
c. Validasi sosial berubah menjadi kompetisi terselubung
Beberapa posting yang diamati cenderung memicu dinamika kompetitif dengan istri pertama:
menampilkan diri lebih lembut,
lebih patuh,
lebih syar’i,
lebih “damai”,
lebih “ideal”.
Namun perlu dipahami, kesan ideal itu sering muncul karena fase hidup yang masih ringan—belum dihadapkan pada beban rumah tangga penuh, rutinitas yang melelahkan, atau dinamika pernikahan jangka panjang.
Yang terlihat adalah versi terbaik dari seseorang,
bukan gambaran sebenarnya ketika tanggung jawab, tekanan, dan ritme hidup mulai berbagi ruang.”


6. Dampak pada Istri Pertama: Luka yang Tak Dianggap Penting
Bagi istri pertama, fenomena ini mengguncang secara emosional.
Mereka tidak hanya kehilangan kepercayaan pada suami, tetapi juga merasa:
ditantang oleh sosok yang tampak lebih “salehah”,
disudutkan secara moral,
dihadapkan pada kompetisi yang tidak pernah mereka minta,
dipaksa menerima narasi “ini sunnah”.
Ketika perempuan kedua memamerkan perannya, meski secara halus, luka itu semakin dalam.
Fenomena ini bukan masalah kecemburuan, tetapi ketidakadilan emosional yang disucikan dengan dalil


7. Dampak pada Anak: Luka Sunyi yang Tidak Selalu Terlihat
Konflik yang terjadi tanpa transparansi—kedekatan yang disembunyikan, perubahan sikap tiba-tiba, atau keputusan besar yang berjalan samar—sering menyisakan luka paling dalam pada anak-anak.
Mereka mungkin tidak memahami apa yang terjadi,
tetapi mereka merasakan:
perubahan suasana rumah,
wajah ibu yang semakin lelah,
ayah yang sering tidak hadir,
dan ketegangan yang tak pernah dijelaskan.
Anak-anak belajar tentang komitmen, kejujuran, dan cinta
dari apa yang dilihat setiap hari.
Ketika konflik berlangsung lama, itu dapat memunculkan:
rasa tidak aman,
perubahan perilaku,
penurunan konsentrasi belajar,
kemarahan yang bingung ditujukan ke siapa.
Dan yang paling menyedihkan:
mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta bisa datang bersama penolakan dan pengkhianatan.


8. Dampak pada Keluarga Besar: Gelombang yang Merambat Lebih Luas
Di banyak keluarga Indonesia yang komunal,
ketika poligami terjadi tanpa proses yang rapi dan terbuka,
keluarga besar sering ikut merasakan getarannya:
hubungan antar mertua merenggang,
adik-kakak terbelah opini,
suasana silaturahmi berubah,
keluarga bingung harus berdiri di mana,
muncul rasa sungkan atau ketegangan berkepanjangan.
Ketidakjelasan proses membuat keluarga besar kehilangan pegangan
tentang apa yang sebenarnya terjadi—
dan sering kali mereka hanya bisa menyaksikan luka itu dari jauh
tanpa bisa melakukan apa-apa.
9. Dampak pada Masyarakat: Retaknya Kepercayaan terhadap Komunitas Hijrah
Ketika pola ini muncul berulang di berbagai majelis, komunitas, atau lingkungan hijrah, masyarakat mulai bertanya:
Mengapa polanya mirip?
Mengapa prosesnya samar?
Apakah ini masalah ajaran atau cara orang menjalankannya?
Jika tidak direspons dengan jernih,
dapat timbul:
persepsi negatif terhadap komunitas dakwah,
sinisme pada simbol-simbol kesalehan,
distrust terhadap pembimbing agama,
kekhawatiran perempuan ikut kajian tertentu,
stigma terhadap perempuan baru hijrah.
Padahal persoalannya bukan pada ajaran Islam,
melainkan cara sebagian orang memanfaatkan citra agama
untuk membungkus proses yang tidak sehat.
Dengan demikian, dampaknya bukan hanya personal,
tetapi menyentuh lanskap sosial yang lebih luas.
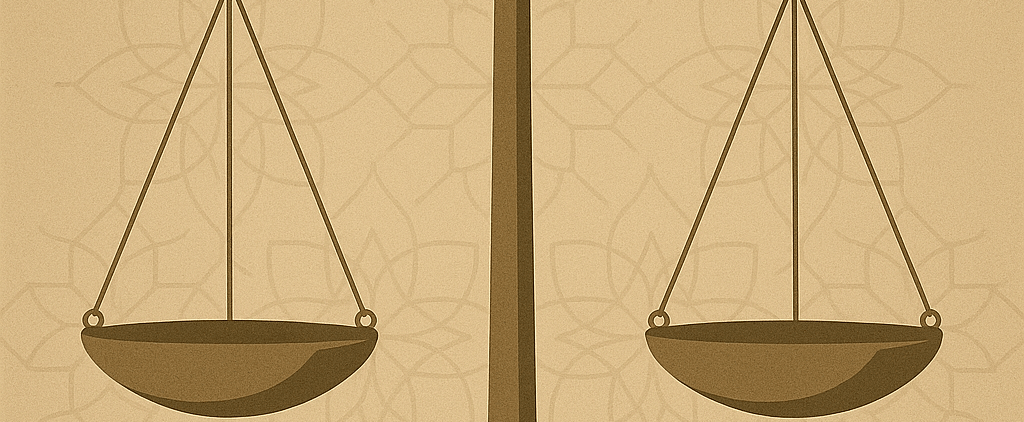

10. Fenomena Baru Kesalehan Digital: Saat Iman Bergeser Menjadi Tampilan
Setelah melihat bagaimana dampak dari proses yang tidak sehat dapat merambat dari pasangan, anak, keluarga besar, hingga masyarakat, pertanyaannya kembali ke akar persoalan:
apa yang sebenarnya mendorong pola-pola ini berulang di banyak tempat?
Salah satu jawabannya terletak pada fenomena yang kian menonjol hari ini:
kesalehan yang tampil, bukan hanya dijalani.
Di era digital, perjalanan hijrah tidak lagi bergerak sepenuhnya di ruang sunyi, pribadi, dan perlahan seperti dulu. Kini ia berlangsung di ruang yang terang, terbuka, dan sering kali berkaitan dengan impresi publik.
Kebaikan tentu tetap ada — bahkan sangat banyak.
Tetapi di balik itu, ada dinamika baru yang pelan-pelan muncul:
a. Kesalehan yang Terlihat Lebih Mudah Mendapat Validasi -Media sosial memberi ruang untuk hal ini
b. Ruang Kajian yang Semakin Dekat dengan Ruang Personal
c. Persona Syar’i yang Tidak Selalu Sama dengan Watak Sehari-Hari
d. Kebaikan yang Aslinya Tulus, tetapi Dinikmati dengan Cara yang Salah
11. Bukan Semua Poligami Buruk — Justru Poligami Terhormat Perlu Dibedakan
Esai ini tidak menuduh bahwa semua poligami modern salah.
Sebaliknya, ada poligami yang dijalankan dengan:
kejujuran,
restu istri pertama,
proses resmi,
komunikasi matang,
tanpa selingkuh sebelumnya,
dan semua pihak masuk dengan kesadaran penuh.
Poligami seperti ini terhormat.
Tidak menjadikan perempuan terluka, tidak memanipulasi dalil, tidak bermain dalam gelap.
Justru agar poligami yang benar dihormati,
fenomena poligami manipulatif perlu dibedakan secara jernih.


Penutup: Untuk Menjernihkan, Bukan Menyudutkan
Fenomena poligami modern, terutama ketika berkaitan dengan hijrah dan ruang digital, menuntut kejujuran lebih dari sekadar dalil.
Yang dipersoalkan bukan jumlah istri,
tetapi integritas cara menjalankannya.
Poligami Rasulullah adalah amanah sosial.
Poligami sebagian orang hari ini adalah pelarian emosional yang didekorasi ayat.
Maka pertanyaan yang patut direnungkan bukanlah:
“Bolehkah poligami?”
Tetapi:
“Apakah cara menjalankannya mencerminkan akhlak Nabi atau hanya mengambil nama beliau untuk menutupi yang gelap?”
Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan status suami atau istri,
melainkan kemampuan menjaga hati manusia yang Allah titipkan.
Ditulis oleh: Tim Redaksi TapisDigital
Refleksi atas fenomena sosial-keagamaan di era digital.
Referensi & Bacaan Tambahan
Sirah Nabawiyah
Ar-Rahiq Al-Makhtum
Tafsir Ibn Katsir
Fathul Bari
Kajian akademik tentang gerakan hijrah dan religiositas digital di Indonesia (UI, UGM, UIN).
Artikel psikologi keluarga tentang dinamika relasi, validasi sosial, dan komunikasi digital.
Artikel Lainnya
Berita dan artikel dengan perspektif inklusif.
Komunitas
Info Terkini
redaksi@tapisdigital.id
+62 895-1440-2290
© 2025. All rights reserved.
